Sorry, we couldn't find any article matching ''
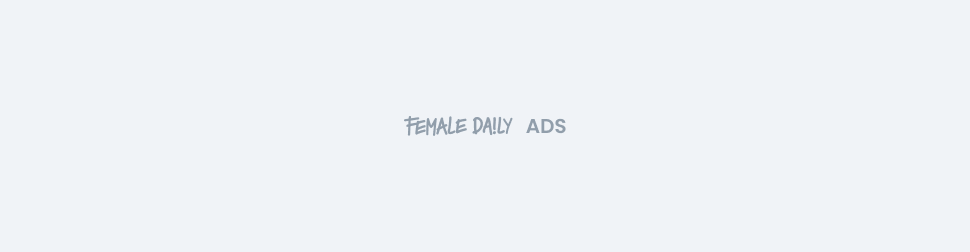
Hari Ibu Bukan Sekadar Bunga dan Ucapan, Ada 7 Makna Lain di Balik Itu
Bukan hanya soal mengucapkan “Selamat Hari Ibu” dan memberi bunga pada ibu kita, tapi Hari Ibu juga punya makna yang lebih berharga.
Setiap 22 Desember, kita memperingati Hari Ibu. Media sosial dipenuhi unggahan kata-kata indah tentang pengorbanan seorang ibu. Ibu digambarkan sebagai sosok yang selalu kuat, sabar, penuh kasih, dan nyaris tanpa cela. Namun di balik perayaan itu, ada kenyataan yang jauh lebih kompleks dan sering kali luput dibicarakan.
Bagaimana jika Hari Ibu tidak hanya kita rayakan, tetapi juga kita renungkan? Bagaimana jika momen ini menjadi ruang untuk melihat ibu—dan peran keibuan—secara lebih utuh dan manusiawi? Tulisan ini mengajak kita menengok sekian hal lain yang tersembunyi di balik peran seorang ibu: hal-hal yang jarang dibicarakan, namun sangat menentukan kualitas hidup perempuan dan keluarga.
BACA JUGA: Daftar 7 Promo Spesial di Hari Ibu 2025, Pas untuk Kado!
1. Beban Mental yang Tak Terlihat
Di media sosial, kita melihat fenomena mom influencer, di mana pengalaman menjadi ibu dikemas, ditampilkan, dan sering kali dipoles menjadi konten yang menarik, inspiratif, sekaligus menjual. Di satu sisi, mereka membuka ruang representasi: berbagi tips, solidaritas, dan rasa “saya tidak sendirian” bagi banyak perempuan.
Namun di sisi lain, narasi yang dominan kerap mereproduksi standar ibu ideal—tetap sabar, produktif, rapi, dan kinclong di tengah beban yang berat. Kelelahan ditampilkan, tetapi sering kali sudah diberi bingkai estetik; kesulitan diakui, namun segera ditutup dengan pesan afirmatif agar tetap terlihat kuat.
Tanpa disadari, fenomena ini memperhalus tekanan sosial baru bagi para ibu: bahwa bahkan dalam lelah pun, mereka diharapkan tetap tampil glowing dan menginspirasi. Di permukaan tampak “everything is under control”, padahal siapa yang benar-benar tahu?
2. Dilema Diri dan Konflik Identitas
Konflik diri kerap hadir. Bekerja memunculkan rasa bersalah pada anak. Tidak bekerja, muncul rasa bersalah pada karier dan diri sendiri. Bahkan kesenangan pun bisa memicu rasa bersalah, seolah ibu tidak sepenuhnya berhak menikmati hidup. Rasa bersalah ini menjadi bayangan yang terus mengikuti, apa pun pilihan yang diambil.

Foto: Freepik
3. Relasi yang Tidak Setara
Pengasuhan masih dianggap tugas utama perempuan. Ketika ayah terlibat, ia sering dipuji sebagai sosok yang “membantu”, sementara keterlibatan ibu dianggap kewajiban. Standar yang timpang ini membuat tuntutan terhadap ibu begitu tinggi, sementara ekspektasi terhadap ayah cenderung rendah dan longgar. Standar ganda ini masih mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kesepian Emosional
Tak sedikit ibu mengalami kesepian emosional. Merasa sendirian, tidak didengar, tidak benar-benar ditanya apa yang mereka butuhkan. Kebutuhan pribadi kerap ditunda, bahkan dilupakan, demi menjaga keseimbangan keluarga dan memenuhi kebutuhan orang lain.
5. Warisan Luka Antar Generasi
Cara kita memaknai keibuan kerap diwariskan dari ibu dan nenek kita. Di balik warisan itu, ada luka yang berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cara ibu saya memperlakukan saya, sering kali bukan semata-mata tentang saya, melainkan manifestasi dari kekecewaan dan luka yang tak sempat ia pahami atau pulihkan. Tanpa saya sadari, saya tumbuh membawa luka tersebut, dan berisiko memproyeksikannya kembali kepada anak. Begitulah pola itu berulang dan terus hidup lintas generasi.

Foto: senivpetro/Freepik
6. Relasi Ibu–Anak yang Tidak Selalu Ideal
Hari Ibu juga bukan hari yang sederhana bagi semua orang. Tidak semua memiliki relasi hangat dengan ibunya. Ada yang dibesarkan oleh ibu non-biologis, ada yang kehilangan ibu, ada pula yang hidup dengan relasi penuh jarak, luka, atau “perang dingin” yang panjang. Ada cinta, tetapi juga ada rasa bersalah, penyesalan, dan kata-kata yang tak pernah sempat terucap.
7. Ibu yang Tak Terlihat
Ibu non-biologis, ibu angkat, nenek, tante, pengasuh—mereka merawat, membesarkan, dan hadir, namun sering kali luput dari perayaan. Di saat yang sama, ada pula perempuan yang memilih untuk tidak menjadi ibu. Pilihan ini masih kerap dipandang egois atau tidak utuh, padahal ia juga merupakan bentuk kejujuran dan tanggung jawab. Tidak semua orang ingin atau mampu menjalani peran ini, dan memaksakannya hanya akan melahirkan luka baru.
Ada perempuan yang menjadi guru, mentor, pendamping, atau figur pengasuhan bagi banyak orang: memberi arah, perhatian, dan kasih sayang dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin tidak melahirkan kita, tetapi menjalankan peran keibuan: mengasihi, membimbing, menumbuhkan potensi, dan hadir secara penuh dalam kehidupan kita.
Hari Ibu seharusnya menjadi lebih dari sekadar perayaan simbolik. Ia bisa menjadi momen refleksi: tentang sistem yang kita warisi, tentang pembagian peran yang belum adil, tentang keberanian melepaskan narasi lama yang menempatkan perempuan sebagai penyangga utama segalanya. Juga tentang upaya menyembuhkan luka inner child yang bersumber dari relasi dengan ibu—baik luka yang kita terima, maupun yang tanpa sadar kita wariskan.
Menghormati ibu tidak cukup dengan bunga setangkai atau ucapan setahun sekali. Ia juga terwujud dalam penerimaan terhadap pilihan hidupnya, dalam usaha kita menjadi pribadi dengan versi terbaik diri sendiri, sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan caranya.
Mungkin, di sanalah makna Hari Ibu yang lebih jujur bisa kita temukan.
Cover: tirachardz/Freepik
Share Article


POPULAR ARTICLE




COMMENTS