Sorry, we couldn't find any article matching ''
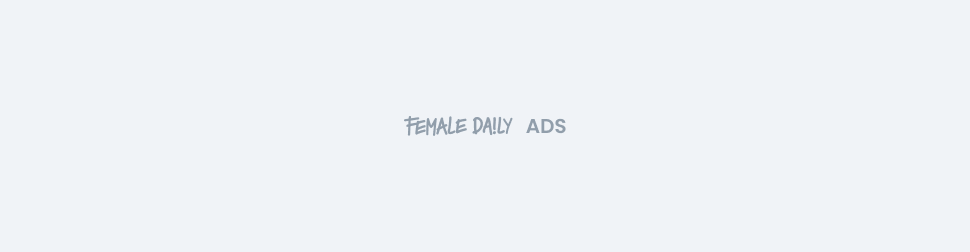
Mengenal Quiet Quitting, Benarkan Bisa Membuat Hidup Lebih Seimbang?
Gembar-gembor terhadap work life balance akhirnya melahirkan suatu budaya kerja baru di kalangan profesional muda: quiet quitting. Mari pahami lebih jauh.
Belakangan istilah quiet quitting ramai jadi perbincangan di media sosial. Bukan, istilah ini bukan berarti resign diam-diam dari pekerjan. Melainkan, meninggalkan ritme kerja hustle culture yang serba cepat, sibuk dengan jam kerja yang lebih panjang, dan beralih ke budaya kerja yang sesuai dengan job desc dan jam kerja yang ditetapkan. Nggak kurang, nggak lebih, sesuai dengan gaji yang dibayarkan.
Walau istilah ini baru muncul, tapi konsep bekerja seperti ini bukan hal baru. Video yang diunggah @zaidleppelin pada Juli 2002 lalu-lah yang membuat istilah quiet quitting viral dan kemudian jadi tren di kalangan profesional muda, yaitu generasi milenial dan gen Z. Seperti apa, sih, quiet quitting itu?
Ciri-ciri budaya kerja quiet quitting
Nggak ada definisi baku tentang quiet quitting, namun ada ciri-ciri yang amat jelas tentang gaya kerja yang dianggap lebih tenang ini.
Para pekerja yang menerapkan gaya kerja ini menolak untuk bekerja melampaui tugas dan tanggung jawab mereka, nggak ambisius, nggak mau bekerja di luar jam kerja dan penuh tekanan. Ini adalah bentuk “berhenti” dari budaya kerja ambisius yang dianggap melelahkan bagi fisik maupun mental. Cukup lakukan tugas dan tanggung jawab, lalu selesai, nggak perlu do extra.
Penganut sistem kerja seperti ini meyakini bahwa ada kehidupan di luar kantor yang harus diperhatikan juga. Ada keluarga, hobi, dan mungkin ada usaha atau usaha lainnya yang membutuhkan waktu dan perhatian. Nggak mau menghabiskan waktu dan energi hanya untuk perusahaan tempat bekerja semata.
Plus minus tren kerja quiet quitting
Bagi beberapa orang, menerapkan sistem kerja yang lebih tenang ini dianggap baik untuk kesehatan mental. Alex Bauer, seorang pekerja di Wisconsin, Amerika Serikat, telah meninggalkan budaya hustle culture di tempat bekerja yang lama dan sudah menerapkan quiet quitting di tempat kerja yang baru selamat empat bulan. Ia mengaku nggak lagi mengalami anxiety attacks. Kini dia bekerja 40 jam seminggu, dan tak ada lagi tuntutan emosional dalam pekerjaannya. Ia hanya menjalankan tanggung jawab, pulang ke rumah, dan nggak mikirin kerjaan lagi di rumah. Bahkan, ia bisa mengurusi bisnis sampingannya.
Jika disimpulkan, sisi positif dari budaya kerja quiet quitting ini membuat pekerja jadi memiliki hidup lebih seimbang, stres karena pekerjaan jadi lebih rendah, mengenali batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tujuan akhirnya, pekerja memiliki mental yang lebih sehat.
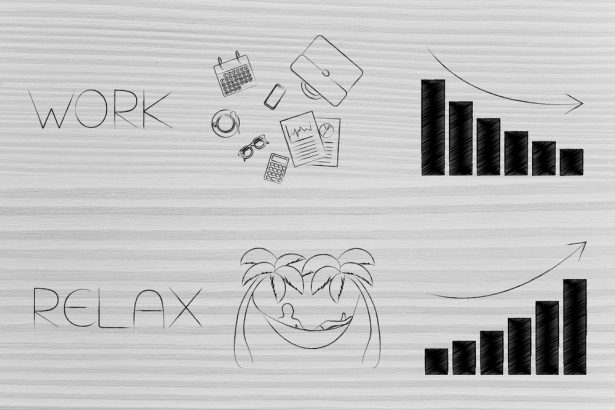
Di sisi lain, gaya kerja seperti ini juga berarti bersikap nggak mau terlibat lebih dalam pekerjaan. Maggie Perkins, seorang guru (30) yang sudah empat tahun bekerja dengan gaya quiet quitting ini mengaku nggak mau lagi jadi sukarelawan di komite-komite sekolah. Ia hanya mengajar dan jadi guru yang baik saja di sekolah. Demikian halnya dengan Paige West (24), nggak lagi mengikuti berbagai training dan berhenti berupaya untuk bersosialisasi dengan para kolega.
Tindakan ini bisa membuat pekerja jadi less-enagaged di pekerjaan dan di perusahaan. Karyawan menanggalkan seluruh sisi emosi di dalam pekerjaan, kemudian jadi nggak bisa menemukan sukacita dan hanya menjalani kewajiban belaka. Akhirnya, pekerja kehilangan sense of meaning and belonging di dalam pekerjaan yang akhirnya membuat karir bisa menjadi stagnan.
Baca juga: Matriks Eisenhower untuk Menentukan Prioritas Kerja
Apa kata para ahli tentang tren quiet quitting?
Melansir NY Times, Menurut Matt Spielman, seorang career coach di New York City dan penulis buku Inflection Points: How to Work and Live With Purpose, budaya kerja baru ini ada kaitannya dengan burnout di pekerjaan yang terjadi selama pandemi. Akibatnya, orang jadi ingin mundur sejenak, dan mengambil langkah yang lebih lambat. Menurutnya, ini adalah hal wajar.
Namun Spielman merasa tindakan quiet quitting ini juga terkesan sebagai tindakan pasif agresif dari para karyawan sebagai cara untuk membalas perusahaan. Jika seorang karyawan merasa overload dan kelelahan, hal yang tepat untuk dilakukan adalah berbicara dengan atasan atau HRD dan mengutarakan keberatannya, dan mencari jalan keluar, ketimbang menjadi less engaged secara drastis karena merasa itu adalah haknya sebagai karyawan.
Bagi Jaya Dass, Managing Director Randstad untuk Singapura dan Malaysia, ini merupakan salah satu dampak dari Covid-19 dan Great Resignation akibat pandemi. Karyawan merasa berhak untuk mengendalikan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Bekerja dengan jam kerja, porsi dan tekanan yang normal kini nggak lagi sebatas harapan dari karyawan, melainkan tuntutan.
Michael Timmes, seorang Senior HR Specialist menambahkan, bahwa ada perbedaan besar antara ingin meraih work life balance yang lebih baik dengan menjadi pekerja pasif. Sebetulnya, bisa banget bekerja secara optimal di jam kerja di kantor tanpa lembur dengan tetap terlibat dan memaksimalkan potensi. Sayangnya, mentalitas ini belum ada pada orang-orang yang melakukan tren quiet quitting ini.
Para ahli sepakat, sikap quiet quitting ini bisa jadi backfire. Anggota tim lain akan menganggap pekerja nggak terlibat, dan bekerja seadanya, kemudian timbul konflik. Pekerja nggak lagi merasa bangga atas apa yang telah dilakukan, bahkan kehilangan gairah kerja. Pada akhirnya, orang yang akan berhasil tentunya orang yang menunjukkan etos kerja yang bagus dan mau bekerja extra miles, bukan yang bekerja seadanya.
Baca juga: Penerapan Konsep Ikigai Dalam Dunia Kerja, Bisa Tingkatkan Semangat Kerja
Jadi, harus bagaimana?
Apapun istilahnya, saya, sih, setuju banget dengan budaya kerja yang tetap mengedepankan work life balance. Antara pekerjaa, keluarga dan kehidupan pribadi sama-sama penting dan punya prioritas yang setara. Ada kalanya kita mengalahkan pekerjaan demi keluarga, atau sebaliknya, mengutamakan menyelesaikan pekerjaan, setelah itu baru urus urusan pribadi.
Tapi ingat, kalau mau berhasil dan naik level, yaaa, memang ada harga yang harus dibayar. Harus bersedia go extra miles. Terlalu strict dengan jam kerja dan nggak mau berbuat lebih juga akan bikin kita stuck di satu posisi dan nggak ada kemajuan. Intinya, menerapkan work life balance nggak berarti kaku banget sama jam kerja dan jadi menolak untuk mengerjakan lebih. Sementara, menerapkan hustle culture juga bukan jaminan itu akan mengantarkan kita pada keberhasilan.
Balik lagi, time and priority management kitalah yang bisa membuat kita mengatur pekerjaan dengan baik. Kita hanya perlu menerapkan apa yang nyaman buat kita, dan tahu cara menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, tanpa perlu terjebak dengan hustle culture atau jadi terlalu extreme dengan quiet quitting.
Gimana menurut mommies? Kita diskusi di kolom komentar, yuk!
Baca juga: Jerat The Hustle Culture yang Menghancurkan Hidup Kita Tanpa Sadar
Share Article




COMMENTS