Sorry, we couldn't find any article matching ''
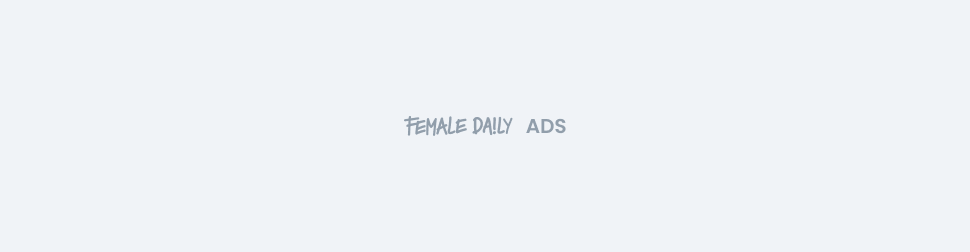
Fenomena Latte Dad di Swedia dan Kontrasnya dengan Fatherless di Indonesia
Fenomena Latte Dad di Swedia menunjukkan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Di Indonesia, angka fatherless masih tinggi. Sudah saatnya ayah lebih hadir.
Mommies, pernah dengar istilah Latte Dad? Bayangkan seorang ayah muda di Stockholm, mendorong stroller sambil nyeruput kopi latte di taman. Itu bukan berarti si Ayah lagi liburan apalagi sedang nggak punya pekerjaan ya, Mommies. Si Ayah bisa begitu karena sedang cuti kerja untuk mengasuh bayinya. Pemandangan seperti itu sudah jadi hal lumrah di Swedia — sebuah negara yang menjadikan peran ayah dalam pengasuhan anak sebagai bagian penting dari kebijakan sosialnya.
Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Di sini, masih banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah — secara fisik dan atau emosional. Fenomena ini bahkan punya istilah tersendiri yaitu fatherless. Dua kata yang menggambarkan dua dunia berbeda tentang ayah ini: keluarga, dan pengasuhan.
BACA JUGA: Paternity Leave: Mengapa Cuti Ayah Penting? Ini Jawaban Langsung dari Para Ayah
Apa Itu Latte Dad?

Foto: Freepik
Istilah Latte Dad muncul di Swedia untuk menyebut para ayah yang mengambil cuti ayah dan ikut terlibat secara aktif mengasuh anak. Biasanya, mereka terlihat di kafe atau taman bersama bayi mereka — simbol baru dari keseharian yang menjadi tanda perubahan besar dalam budaya pengasuhan anak.
Di balik fenomena ini, ada sistem yang mendukung. Pemerintah Swedia memberikan 480 hari cuti orang tua berbayar untuk setiap anak, yang bisa digunakan hingga sang anak berusia 12 tahun. Tak hanya itu, sebagian jatah cuti wajib digunakan oleh sang ayah — kalau tidak, hak cuti itu bakal hangus. Ayah mana yang, nggak, happy coba?
Kebijakan ini terbukti mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran ayah. Tahun 1974, ketika cuti orang tua pertama kali diperkenalkan, hanya 1% dari cuti itu digunakan oleh pria. Namun kini, sekitar 30% hari cuti diambil oleh ayah. Setelah tahun 1995, ketika pemerintah menambahkan 30 hari khusus untuk laki-laki, angka partisipasi langsung melonjak ke 75%.
Fenomena ini melahirkan sosok Latte Dad yang dianggap simbol modernitas, para ayah yang tak hanya wajib menafkahi keluarga, tetapi juga hadir secara penuh dalam kehidupan anak mereka.
Manfaat Latte Dad
Bukan cuma gaya hidup, menjadi Latte Dad ternyata membawa banyak manfaat — bukan hanya untuk anak, tapi juga bagi si ayah sendiri, keluarga, bahkan masyarakat secara luas.
1. Untuk anak:
- Anak yang memiliki ayah aktif cenderung lebih sukses di sekolah dan punya keterampilan sosial lebih baik.
- Interaksi intens dengan ayah di usia dini terbukti meningkatkan perkembangan kognitif anak.
- Hubungan emosional yang kuat antara ayah dan anak membentuk rasa aman dan percaya diri dalam diri anak.
2. Untuk ayah:
- Cuti panjang untuk terlibat dalam pengasuhan anak bisa memperbaiki kesehatan mental dan fisik. Sebuah studi bahkan menemukan bahwa tingkat rawat inap terkait alkohol menurun di kalangan ayah yang mengambil parental leave.
- Waktu bersama anak membuat ayah lebih memahami betapa sulitnya mengasuh anak sambil membangun hubungan yang lebih dalam dengan keluarga.
- Banyak Latte Dad mengaku pengalaman ini membuat mereka lebih sabar, lebih berempati terutama kepada pasangan mereka, dan menghargai peran pasangan.
3. Untuk keluarga dan masyarakat:
- Pembagian tanggung jawab yang lebih setara membuat hubungan suami dan istri lebih harmonis.
- Masyarakat jadi lebih terbuka terhadap konsep gender equality dalam keluarga.
- Lahir budaya baru yang melihat “maskulinitas” bukan dari seberapa keras seorang pria bekerja, tapi seberapa hadir ia untuk anaknya.
Fatherless di Indonesia: Realitas yang Berbeda

Foto: Freepik
Sekarang mari lihat ke sisi lain dunia, yaitu Indonesia. Menurut data BKKBN, sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran aktif seorang ayah. Artinya, satu dari lima anak di negeri ini hidup dalam kondisi fatherless. Angka ini cukup tinggi dan berdampak langsung pada perkembangan anak, baik secara emosional, sosial, maupun akademik. Penyebabnya kompleks:
- Budaya patriarki masih kuat. Ayah dianggap hanya bertugas mencari nafkah, sementara pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan ke ibu.
- Faktor ekonomi dan jam kerja panjang membuat banyak ayah nggak punya waktu dan tenaga lagi untuk berinteraksi dengan anaknya.
- Perceraian, kematian, atau pekerjaan yang mengharuskan ayah tinggal jauh dari keluarga.
- Dan tentu, minimnya dukungan kebijakan. Cuti ayah di Indonesia biasanya hanya beberapa hari, jauh dari cukup untuk membangun keterikatan emosional dengan bayi baru lahir.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan hanya 37,17% anak usia di bawah lima tahun yang diasuh oleh kedua orang tuanya secara bersamaan. Sisanya tumbuh dengan kehadiran dominan dari salah satu pihak — biasanya ibu.
Dampak Fatherless pada Anak
Ketiadaan figur ayah tak hanya soal siapa yang ada di rumah, tetapi juga siapa yang hadir secara emosional. Berbagai penelitian, termasuk dari UNICEF, menunjukkan anak yang tumbuh tanpa figur ayah rentan mengalami:
- Masalah emosional dan psikologis: harga diri rendah, depresi, atau rasa marah dan kehilangan arah.
- Kesulitan sosial: anak bisa sulit berinteraksi, cenderung agresif, atau sulit membangun hubungan dekat.
- Prestasi akademik yang menurun: karena kurang dukungan dan bimbingan dari figur ayah.
- Masalah identitas: anak kehilangan panutan tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai maskulinitas yang sehat.
Bukan berarti anak fatherless tak bisa tumbuh bahagia. Namun, mereka membutuhkan dukungan emosional yang konsisten dari lingkungan sekitar agar tumbuh kembangnya tetap optimal.
Menyembuhkan dan Menghadirkan Kembali Sosok Ayah
Menyadari adanya fenomena fatherless bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk menemukan solusi. Langkah pertama adalah menyadari kebutuhan emosional anak dan berusaha hadir buat anak, bahkan jika secara fisik ayah tidak selalu bisa ada di rumah.
Beberapa hal yang bisa dilakukan:
- Bangun hubungan suportif: hadirkan figur anggota keluarga laki-laki seperti kakek, paman, atau mentor, Ini dapat memberikan rasa aman pada anak.
- Ciptakan komunikasi terbuka: dengarkan curahan hati anak tanpa menghakimi.
- Berikan kasih sayang tanpa syarat: kehangatan dan perhatian bisa menggantikan banyak kekosongan emosional.
- Libatkan komunitas dan konselor: dukungan sosial sangat membantu anak memahami dan mengelola perasaannya.
- Kegiatan positif: misalnya mengajak anak berolahraga, ikut kelas musik, melukis, atau bahkan belajar coding — aktivitas ini menumbuhkan rasa percaya diri dan mental yang kuat.
Saatnya Kita Belajar dari Swedia

Foto: Freepik
Fenomena pengasuhan anak Latte Dad di Swedia menunjukkan bahwa kebijakan sosial bisa mengubah wajah keluarga. Ketika negara memberi waktu dan ruang bagi ayah untuk ikut membesarkan anak, hasilnya tak hanya terasa di rumah, tetapi juga di masyarakat.
Indonesia mungkin masih jauh dari kebijakan parental leave yang ideal, tapi perubahan bisa dimulai dari langkah kecil: dari para ayah yang mau lebih hadir, dari perusahaan yang mulai memberi cuti ayah lebih panjang, dan dari masyarakat yang harus berhenti menghakimi bahwa “ayah yang aktif mengasuh anak” itu nggak manly.
Karena pada akhirnya, baik Latte Dad maupun para ayah di Indonesia punya tujuan yang sama: mencintai dan membesarkan anak-anak mereka sebaik mungkin. Hal yang membedakan hanyalah soal dukungan, kesempatan, dan kemauan kuat untuk hadir sepenuhnya buat anak.
BACA JUGA: 7 Alasan Anak Tidak Dekat dengan Ayah, Bisa Alami Fatherless hingga Daddy Issue
Cover: Freepik
Share Article


POPULAR ARTICLE




COMMENTS