Sorry, we couldn't find any article matching ''
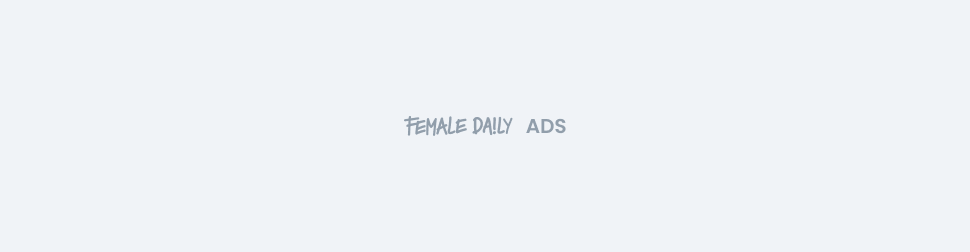
Sebenarnya, Seberapa Siapkah Kita Jadi Orangtua?
‘Penyakit’ orangtua modern, kata filsuf Alain de Botton, terobsesi menjadi orangtua yang sempurna. Perhatian dan kasih sayang dicurahkan sepenuhnya, di setiap detail kehidupan anak. “Hanya untuk memutuskan menu apa yang akan diberikan ke anak untuk makan malam, bisa sampai berjam-jam memutuskannya,” sindir Alain. Bernada sarkas memang. Tapi ada benarnya, kan.

Kalau dibilang, orangtua sekarang itu enggak tahu apa yang harus disiapkan buat anak, tidak juga. Banyak kok, yang habis-habisan (dan overprotective) demi anak. Tapi, kenyataannya, masih ada saja yang clueless (contoh saja), dalam sebuah pertemuan orang tua murid di sekolah, keluar komen seperti ini:
”Anak saya di rumah kerjaannya ‘tiarap’ melulu. Tolong dong, sekolah kasih tugas, dia harus kirim video lagi belajar, sholat, ngaji. Soalnya, kalau orangtua yang nyuruh, enggak mempan.”
“Bisa nggak sekolah kasih tahu, buku apa yang harus dibaca. Kalau anak suruh inisiatif sendiri, atau orangtua yang kasih motivasi, anak nggak bakal mau.”
“Anak juga harus dikasih materi pelajaran. Diterangkan sampai jelas. Kalau hanya video saja, kurang. Apalagi kalau matematika, IPA.”
Ya, itu hanya contoh saja, situasi umum di masa PJJ seperti sekarang. Rasanya, masa PJJ ini menjadi ujian yang nyata, bagi kaum orangtua, untuk membuktikan, sudah sejauh mana kesiapannya sebagai orangtua?
Menyiapkan mental. Ellen Kristi di buku Cinta yang Berpikir, menyitir pendapat psikolog Kerry Frost, bilang, “Jelas sekali, ada banyak orang yang tidak layak punya anak. Sekadar punya anak itu terlalu gampang. Kalau kalian orang dewasa sedang berencana memiliki anak, tanyalah diri kalian sendiri, apakah kalian siap? Apakah kalian menyimpan trauma masa kecil? Apakah sebagai pribadi kalian mudah sekali meledak marah dan berkata kasar? Kalau kalian masih mengidap gangguan mental, pertimbangkan lagi apa kalian mampu membesarkan anak dengan sikap pengertian dan dukungan emosional yang konsisten.”
Bukan berarti menakut-nakuti, sih, menurut Ellen, hikmah dari apa yang disampaikan Frost adalah supaya menjadi orangtua yang baik, kita tidak boleh hanya mengandalkan impuls alamiah. Alam menyediakan kepada semua ibu dan ayah kapasitas untuk mencintai anaknya, tetapi kita butuh lebih dari sekadar dorongan cinta yang emosional untuk menunaikan amanah itu.
Memahami hakikat anak. “Anak remajaku susah banget diatur. Suruh ini itu nggak mau. Dikasih tahu, ngebantah. Makin besar, kok makin bengal!” curhatan teman, yang nyaris putus asa. Kenapa bisa begitu? Ada baiknya kita memahami hakikat anak. Soal hakikat anak ini cukup banyak dikupas di buku Cinta yang Berpikir. Buat saya, buku ini ibarat ‘buku babon’ parenting, yang sangat memberi insight buat para orangtua.
Salah satu butir pertama, prinsip pendidikan Charlotte Mason, “Anak terlahir sebagai pribadi utuh – mereka bukan lembaran kosong atau embrio yang baru berpotensi menjadi pribadi yang utuh. Mereka adalah pribadi utuh.” Lalu, prinsip kedua, masih tentang hakikat anak, “Anak-anak tidak terlahir sepenuhnya baik atau buruk melainkan menyimpan potensi baik atau buruk.” Di sinilah peran orangtua untuk membantu anak memilih jalan hidup yang mulia. Kalau kita memahami kedua prinsip tersebut, akan lebih mudah untuk bagaimana sebaiknya memperlakukan anak dan di mana harus menempatkan diri kita.
Memahami hakikat pendidikan. Kata ‘pendidikan’ di sini sering dipahami atau berkonotasi dengan sekolah. Asal udah mengirim anak ke sekolah, tugas orangtua sudah selesai. Lantas, tidak banyak orangtua yang mau membekali diri dan belajar tentang hakikat pendidikan.
Ini adalah sebuah salah kaprah yang terjadi di mana-mana. Sejak janin di dalam kandungan, sebagai orangtua, kita sudah dilekati tanggung jawab sebagai pendidik utama. “Mengirim anak ke sekolah itu mudah, tapi menjawab pertanyaan, mengapa saya mengirimnya ke sekolah? Mungkin lebih sulit,” tulis Ellen.
Merumuskan visi pendidikan. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan tentang why-nya, mengapa anak perlu belajar, lalu pertanyaan berikutnya adalah what, apa yang perlu ia pelajari? Dan, how, bagaimana sepatutnya mereka mempelajari itu.
Kemudian, kita perlu belajar tentang teknisnya: bagaimana seni menemani anak belajar. Apa yang perlu dipelajari anak di setiap fase tumbuh kembangnya, tentu berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara belajarnya? Perlukah 24 jam mendampingi anak? Tentu, kembali ke rumusan visi keluarga masing-masing.
Belajar Mengelola Keuangan. Saya pernah dengar keluhan, “Bokek nih aku, habis gaji sebulan buat bayar SPP TK-nya anakku 3 bulan.” Bicara soal keuangan, ini bukan tentang the haves and the have nots. Seringkali soal skala prioritas. Ada yang maksain (walau sebetulnya tak masuk hitungan) masukin anak ke sekolah elit. Di sisi lain, ada yang uangnya habis buat rokok dan jajan di luar, sementara buat anak, boro-boro!
Punya anak berarti saatnya untuk punya persiapan jangka panjang, yang artinya, kita harus rela mengorbankan kenyamanan jangka pendek. Sudah siapkah kita?
Share Article


POPULAR ARTICLE




COMMENTS