Sorry, we couldn't find any article matching ''
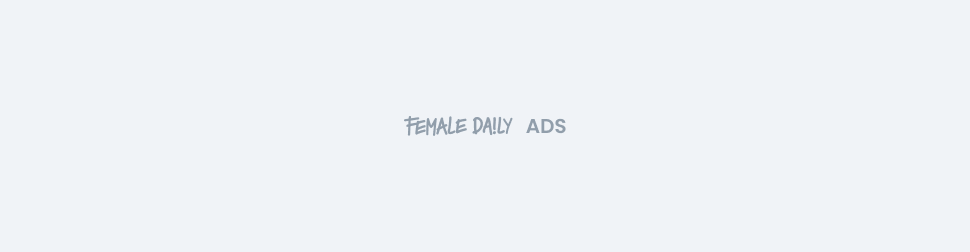
Study-Life Imbalance
Sesuatu yang berlebihan tidaklah baik.
Setidaknya itu yang saya simpulkan dari masa remaja saya dan suami.
Saat SD, saya termasuk anak yang berprestasi di bidang akademik. Sering juara satu di kelas. Hal ini tidak terlepas dari tangan dingin mama saya, yang membuatkan jadwal kegiatan saya sehari penuh, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sudah ranking pun masih disuruh ikut les mata pelajaran, termasuk bahasa inggris, piano, mengaji, belum termasuk ekskul di sekolah seperti menari dan paduan suara. Thank God I enjoyed my busy life, dan masih sempat bermain barbie :)
Masuk SMP, orangtua saya masih menekankan pentingnya prestasi akademik. Les bahasa Inggris dan bimbel masih menjadi menu utama, hanya saja di sekolah saya ikut ekskul paskibraka. Pulang pergi sekolah dan les diantar jemput, sehingga hidup saya hanya sekolah, les, pulang, belajar. Saya sudah keluar dari jajaran sepuluh besar di kelas, tetapi prestasi belajar masih bisa dianggap bagus. Meskipun demikian, saya merasa ada yang timpang. I don’t have good social life, alias enggak gaul, haha…
Menjelang lulus SMP, saya pun bertekad kuat untuk mengikuti sebanyak mungkin ekskul dan organisasi di SMA kelak. Pokoknya, pengen eksis!
Dan, saya membuktikan janji saya tersebut. Saya mengikuti setiap ekskul yang saya minati, gabung di OSIS, berbagai kepanitiaan, termasuk ikut macam-macam kompetisi. Rapor saya? Jarang tembus 15 besar, bahkan sempat bercokol di urutan ke 34, haha.. Tetapi saya tidak menyesal, karena sebagai remaja pada saat itu saya merasakan kebutuhan sosial saya terpenuhi.
Berbeda dengan suami saya. Ia masuk SD favorit, dengan jam belajar hingga sore hari, pengelompokan kelas unggulan dan non unggulan, ternyata membuatnya berpikir “That’s enough, I’m tired”. Akhirnya, ketika SMP ia menjadi kurang semangat belajar dan memutuskan untuk menikmati masa remajanya dengan banyak bergaul, berolahraga, dan ehm…berpacaran. Efeknya, ia merasa bersalah pada sang ayah dan bertekad: pokoknya, SMA saya mau giat belajar! Successfully, he became a study oriented highschooler :p
Dari pengalaman kami yang bertolak belakang, ada satu hal yang menjadi persamaan. Apa itu? Cek di halaman selanjutnya ya!
 *Gambar dari sini
*Gambar dari sini
Bisa diibaratkan, kalau kita yang bekerja mengalami work-life imbalance, maka saya dan suami ketika remaja mengalami study-life imbalance. Kami merasa terlalu banyak belajar, hingga akhirnya yang muncul adalah ketidakpuasan. Ujungnya, kami mencari aktivitas lain yang bisa membuat kami gembira. Naluriah sekali, ya. Syukurlah kegiatan tersebut bukan hal yang negatif dan masih di dalam batas kewajaran.
So, was that our parents’ mistake to send us to the best school, a lot of courses, thus made us study a lot also?
Saya rasa tidak, karena niat semua orang tua adalah baik. They want us to succeed. Hanya saja, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini, ketika anak kita kelak mulai sekolah.
Pertama, pilihlah sekolah yang ramah anak. Kita bisa melihat dari jam belajarnya, aktivitas belajarnya , staf pengajar, hingga kegiatan ekstra yang bisa dipilih oleh siswa. Jam belajar yang terlalu panjang bisa membuat anak lelah, meskipun dari kacamata orang tua kurikulumnya bagus. Apabila memungkinkan, ajak anak memilih sekolahnya. Sekarang banyak sekolah swasta yang menawarkan trial class, sehingga anak bisa merasakan bagaimana kelak proses pembelajaran yang akan ia jalani.
Kedua, jalin komunikasi yang intens dengan anak. Pastikan dari hal tersebut kita bisa mengetahui apakah anak senang atau tidak dengan kegiatannya di sekolah, kursus, maupun pergaulannya, begitu juga dengan siapa teman-temannya dan apa saja yang sering mereka lakukan bersama. Bingung bagaimana cara berkomunikasi dengan anak kita? Artikel “Berbicara Agar Remaja Mau Mendengar dan..” bisa menjadi inspirasi.
Ketiga, walaupun kita produk pendidikan jadul, bear in mind that smart doesn’t mean getting good exam score. Masih banyak orangtua (termasuk saya sendiri) yang kadang terjebak berpikir bahwa nilai pelajaran yang kurang bagus merupakan tanda bahwa si anak kurang cerdas, padahal kita tahu bahwa pandai bergaul merupakan kecerdasan interpersonal dan cepat mempelajari alat musik merupakan kecerdasan musikal. Dengan berpikir bahwa everybody is smart, kita tidak akan memforsir anak kita untuk mahir di satu bidang yang ia tidak suka, atau bukan keahliannya.
So, pandai secara akademis bukan segalanya, yang penting adalah tanggung jawab dengan pilihan yang telah dibuat, dan menjalaninya dengan senang. Setidaknya, dari study-life imbalance saat remaja dulu, saya jadi bisa menemukan apa yang sebenarnya saya suka, dan sejauh mana “dosis” yang tepat untuk melakukannya. Suami pun jadi bisa berempati terhadap orangtuanya yang telah susah payah menyekolahkannya, dan akhirnya “bertanggung jawab” dengan cara kembali belajar dengan benar.
Lessons learned!
PAGES:
Share Article


POPULAR ARTICLE





COMMENTS