Sorry, we couldn't find any article matching ''
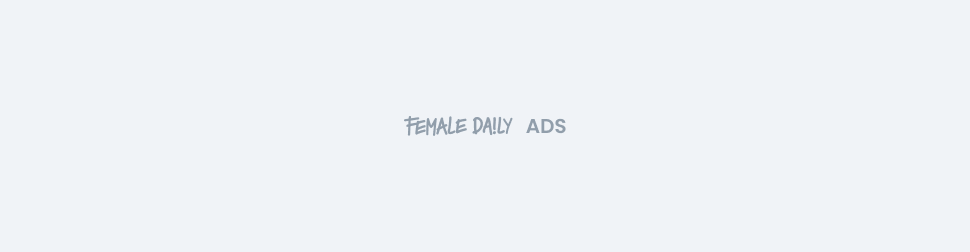
Adeline Windy, Tentang Keberanian Pindah dari Jakarta dan Kekhawatiran Sebagai Single Parent
Terkadang, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Itulah yang dialami oleh Adeline Windy (38). Saat pertama kali mengetahui kehamilan Sora (9 bulan) tanpa pasangan, hidupnya sempat mengalami kekacauan.
Kini, melihat ke belakang, Adel memandang perjalanan hidupnya setelah kehadiran Sora, adalah sebuah keajaiban dan dilimpahi kebahagiaan. Pindah dari Jakarta, ia memulai hidup baru untuk membesarkan Sora seorang diri di Ubud.

Apa yang membuatmu berani memutuskan jadi orangtua tunggal?
Mulanya saya tak ingin jadi single parent. Inginnya ya menikah. Saya juga berat pada awalnya. Saya pernah menikah lalu bercerai di tahun 2014. Tahun 2018, saya ketemu dengan Papanya Sora, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menyudahi hubungan kami.
Setelah bercerai, saya sedang dalam masa transisi yang rasanya tidak sanggup hidup sendiri. Begitu tahu saya hamil, lebih parah lagi. Berat sekali. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk menghadapi kesendirian itu, rasa sedihnya, kecewanya, rasa nelongso, dan bingung, ini mesti gimana.
Momen akhirnya kuat dan bangkit…
Tidak ada momen. Prosesnya itu yang justru membuat saya jadi lebih kuat dan bisa berdiri seperti sekarang. Proses itu pahit banget. Saya sempat dalam keadaan yang sakit secara fisik dan mental. Dan itu menurut saya, saat-saat yang sangat berat. Saya sering mengalami halusinasi.
Misalnya, pintu rumah kok seperti ada yang mengetuk, padahal tidak ada orang. Secara fisik, saya juga sakit-sakitan. Asam lambung saya tinggi. Saya mengalami demam yang berkepanjangan. Padahal di sisi lain, selama hamil itu, saya tetap harus mengajar yoga beberapa kelas setiap harinya. Seperti dilempar oleh semesta. Kalau kamu tidak bisa berjuang, tidak mampu berjuang, selesai hidupmu. Saya betul-betul babak belur. Kabutnya super tebal.

Apa kekhawatiran terbesar setelah mengambil keputusan tersebut?
Dulu kekhawatiran itu ada. Lebih karena saya bekerja untuk masyarakat. Tapi bukan ke dalam, melainkan ke luar. Apakah kalau saya membuka diri, masyarakat akan tetap bisa menerima saya sebagai pengajar yoga. Jujur, ada proses mendalam banget kenapa akhirnya saya putuskan membuka diri.
Saya mau memberi tahu kepada orang, ini bukan sesuatu yang tidak normal. Ini sesuatu yang acceptable. Kita dibentuk oleh budaya sosial. Kalau dipandang dari sisi spiritual, katanya punya anak itu artinya mendapat berkat. Nah, saya sering membalikkan ke orang-orang, kalau kalian menganggap saya nista, artinya Sang Pencipta kalian salah kirim berkat. Kenapa kirim ke saya.
Itu juga sih, salah satu pemikiran yang membuat saya berani terbuka dengan kondisi ini. Dan, setelah saya terbuka, banyak sekali yang kirim DM, para perempuan yang punya kondisi seperti saya, tapi akhirnya dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan.
Alasan pindah ke Ubud
Saya pernah bermimpi, tinggal di Ubud. Pernah bercita-cita punya anak. Tidak terpikir, gimana menikahnya, gimana hamilnya, tapi pingin saja punya anak. Makanya, saya bahagia banget punya anak. Pindah ke Bali, karena saya ingin merawat anak. Begitu hamil, saya merasa, inilah waktunya pindah, mewujudkan angan-angan saya yang dulu.
Saya seperti ditendang oleh semesta, dari Jakarta. Sempat berpikir, kalau pindah, saya meninggalkan banyak kesempatan di Jakarta. Hanya keberanian saja, yang membuat saya bisa settle, seperti sekarang di Ubud. Hanya dengan tabungan yang tidak seberapa, saya pindah begitu saja, cari kontrakan. Waktu itu belum terpikir, nanti di Bali bakal gimana. Ternyata, semesta punya ribuan cara, yang dibukakan kepada saya.
Bagaimana mengatur waktu
Sejak tiga bulan terakhir, saya ditemani seorang asisten rumah tangga. Sebelumnya, segala sesuatu saya kerjakan sendiri. Dalam sehari, saya mengajar beberapa kelas online. Saya menyiapkan konten untuk website pribadi, saya jualan singing bowl, saya yang posting, ngepack dan ngirim.
Saya melibatkan Sora hampir 100%. Ketika mengajar, saya tenteng. Kalau dia nangis, saya bilang, “Sebentar ya, anakku nangis.” Saat dia nggak mau turun, ya tetap saya gendong. Sora selalu bersama saya, termasuk saat saya harus keluar rumah untuk kirim-kirim paket setiap hari, saya bawa dia.
Kadang, saat sedang resah, saya nyetir sama dia ke pantai. Saya tidak melihat Sora sebagai penghalang untuk maju. Saya sering mendengar orangtua bilang gini, “Aku nggak bisa kerja karena ada anak.” Sebagai seorang perempuan, saya tetap punya inner fire untuk bertumbuh. Saya melibatkan Sora dalam seluruh kehidupan saya. Kalau tidak ada Sora, mungkin saya juga tidak akan seperti sekarang.

Sekarang, tantangannya seperti apa
Setelah beberapa bulan di Bali, saya sudah lebih mapan dan lagi seneng-senengnya mengikuti perkembangan Sora. Justru tantangan itu datangnya dari dalam diri, lebih ke mengelola diri, perasaan yang kadang tidak menentu.
Saat saya sedang down, kadang muncul keinginan, “Aku tu ya pingin anakku tu dibawa juga sama bapaknya. Pingin jalan-jalan sama teman-teman bisa gandeng keluarga.” Nah perasaan seperti itu saya akui ada. Itu adalah semata untuk memenuhi ego kita, ingin diakui, diiyakan orang.
Sebetulnya itu buat kepuasan siapa. Seperti, contohnya, anak lagi nangis, kadang berpikir, “Aduh, seandainya ada bapaknya, enak ya. Ada yang bisa diajak gantian.” Padahal di luar sana, banyak juga yang bapaknya ada, tapi anak nangis nggak mau tahu.
Baca juga:
Review Drakor Was It Love: Kisah Cinta Seorang Single Mom
Kekhawatiran Uang Keluarga Modern: Dari Keluarga Lengkap, Single Parent, sampai Sandwich Generation
Lima Jurus Jitu, Mengatasi Situasi Double Income Menjadi Single Income
Share Article


POPULAR ARTICLE




COMMENTS