Sorry, we couldn't find any article matching ''
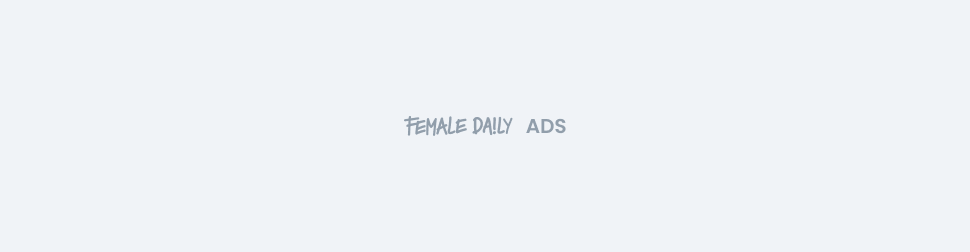
Bully dan Dilema Helicopter Parenting
Ditulis oleh: Ficky Yusrini
Saya tak bermaksud ikut-ikutan mengomentari kasus bully yang sedang viral, tapi saya tertarik mengamati bagaimana reaksi kita para orang tua ketika anak mengalami dan menjadi korban bully.
Baru-baru ini, muncul viral video dua kasus bully yang menjadi sorotan, yakni bully yang dialami mahasiswa pengidap autis oleh teman kampusnya dan yang dialami oleh siswi SMP di Thamrin City. Media sosial pun dipenuhi postingan tentang bully, baik yang pernah dialami sendiri maupun kecaman terhadap pelaku bully.
Saya tak bermaksud ikut-ikutan mengomentari kasus bully yang sedang viral, tapi saya tertarik mengamati bagaimana reaksi kita para orang tua ketika anak mengalami dan menjadi korban bully. Jika hal itu terjadi pada anak Anda, apa yang akan Anda lakukan?
Baca juga:
6 Tantangan Terbesar yang Dihadapi Anak di Sekolah
Saya teringat cerita teman saya, Ana. Tak ingin anaknya yang duduk di kelas 1 SMU, terus-terusan menjadi korban bully di sekolah, ia mencari tahu bocah pelakunya. Suatu kali, Ana nekat mendatangi si pelaku yang sedang makan di warung langganan dekat sekolah. Kebetulan, anak itu rumahnya masih tak jauh dari tempat tinggalnya. Tanpa ba-bi-bu, Ana langsung menanyai si pelaku, alasannya mengganggu Kevin. Geram melihat yang ditanya diam saja, Ana menggebrak meja. “Lain kali kamu masih berani gangguin Kevin lagi, kamu hadapin saya!” ancamnya.
Saya shock mendengar pengakuan Ana. Tak sedikit pun terbersit di benak saya seorang emak-emak datang ‘melabrak’ bocah yang mengganggu anaknya. Tanpa bermaksud judgmental, Ana punya alasan sendiri. Ia mungkin sudah sampai batas putus asa, tak tega anaknya terus-terusan tersakiti. Selain itu, Kevin tumbuh dibesarkan oleh single Mom, sehingga tak memiliki figur laki-laki, terutama ketika menghadapi tekanan dan bully-an.
Kasus lain juga dialami teman saya, Savitri. Anaknya, Irfan, yang masih duduk di bangku SD, mengeluh sering di-bully seorang temannya. Berbagai cara ia lakukan, pendekatan lewat guru di sekolah dan juga pendekatan pada ibu anak yang mengganggu Irfan. Tak percaya setelah diberi tahu apa yang dilakukan anaknya terhadap Irfan, si ibu pelaku malah mengatakan, “Kayaknya nggak mungkin deh, kalau Dean sejahat itu. Lagian, biar mereka sendiri yang selesaikan.” Setelah itu, hubungan si kedua ibu malah jadi memburuk.
Baca juga:
Ketika Anakku Menjadi Pelaku Bully
Saya juga pernah mengalami dilema semacam ini. Suatu kali, anak saya Pi (10 tahun) pulang sekolah berurai air mata, bercerita habis diganggu temannya. Kenakalan seorang temannya itu masih berlanjut hingga beberapa hari. Saya meminta Pi untuk berani menghadapi temannya. Pi tahu betul, saya berhubungan baik dengan ibu temannya itu. Ia pun tercetus, “Ibu, tolong, dong, bilang ke Mamanya si A, biar diingetin sama Mamanya. Aku udah nggak tahan lagi digangguin terus!” Nah, lho! Nyuruh ibunya.
Sebetulnya, saya tidak ingin ikut campur. Saya ingin menunjukkan ke anak bahwa dunia ini tidak bisa berjalan mulus terus, seperti apa yang kita mau. Saya juga ingin ia belajar survival (walaupun jujur, rasanya hati berkeping-keping mendengar tangisannya). Saya maju mundur, antara ingin mengadu ke ibunya bocah, atau menahan diri (lebih lama lagi) sampai anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Syukurlah, akhirnya setelah saya tahan-tahan, pada hari kesekian, bocah mengatakan masalahnya sudah selesai tanpa turun tangan saya. Rasanya saya ikut lega luar biasa.
Sebagai orang tua, saat anak menjadi korban bully, rasanya berada dalam posisi sulit. Seperti makan buah simalakama. Di satu sisi, jika terlalu ikut campur -istilahnya helicopter parenting- anak jadi tidak mandiri. Di sisi lain, jika terlalu dibiarkan menghadapi sendiri, psychological damage-nya terlalu besar. Lantas, mana yang benar? Tidak ada takaran yang pasti, kapan harus campur tangan dan seberapa jauh. Orangtua masing-masing yang seharusnya lebih mengenal daya tahan anak.
Baca juga:
Share Article


POPULAR ARTICLE





COMMENTS