Sorry, we couldn't find any article matching ''
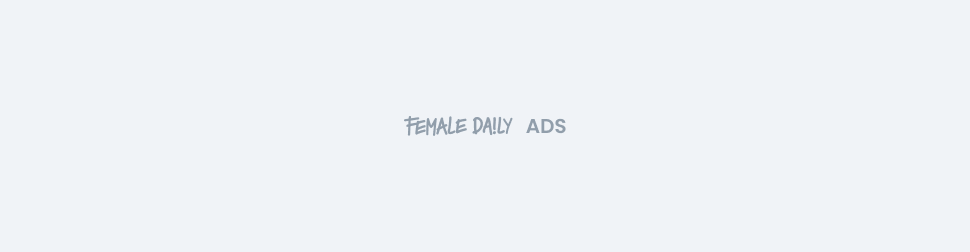
Ayu Oktariani, Taking A Stand Against HIV Stigma
Ayu Oktariani baru tahu dirinya mengidap HIV tahun 2009 saat suaminya yang pernah menjadi pencandu narkoba saat masih sekolah meninggal dunia. Tiga tahun terpuruk, Ayu hingga kini selalu berjuang untuk kesetaraan bagi para ODHA (Orang dengan HIV AIDS).
Ayu sendiri merasakan diskriminasi itu tak hanya datang dari lingkungan, tetapi juga petugas kesehatan yang bahkan “menasihatinya” agar tidak menikah lagi. Padahal ODHA ya sama seperti orang biasa, bisa menikah punya anak, atau menyusui.
Saya kenal Teh Ayu (begitu saya biasa menyapanya) dari komunitas blogger. Sekilas, Teh Ayu sama seperti teman saya yang lain, ia selalu terlihat ceria dan senang mengobrol (seperti saya hahaha). Namun jika mengintip akun Instagramnya @ayuma_morie, terlihat jelas bahwa Teh Ayu memperjuangkan sesuatu yang masih selalu dianggap tabu bagi masyarakat kita: HIV, seksualitas, dan gender.
Simak wawancara saya dengan Teh Ayu berikut ini.
Teh Ayu, lagi sibuk apa? Boleh diceritain kegiatan sehari-harinya?
Sekarang ini lagi sibuk berwirausaha sama suami di Bandung. Kebetulan sekarang kami mengelola café kopi, warung siomay juga punya akademi futsal untuk anak-anak dan remaja. Selain lagi asyik-asyiknya menjalani usaha bersama pasangan, sekarang ini saya juga bergabung dengan klub menulis bernama CS Writers Club. Kita kumpul setiap hari Kamis, menulis dengan tema yang berbeda dan tentunya berkumpul dengan banyak orang dari beragam latar belakang.
Saat ini saya juga bekerja untuk sebuah ruang kreatif yang diinisiasi oleh Pemerintah kota Bandung pada era Kang Emil (Ridwan Kamil). Namanya Bandung Creative Hub. Saya bekerja di divisi media dan publikasi. Jadi pengalamannya makin bertambah dengan menggeluti bidang kreatif.
Yang paling seru, sekarang rutin membuat sebuah inisiatif bersama lima orang sahabat yang kemudian kami namakan Panggung Minoritas. Inisiatif ini akan banyak mengulas obrolan obrolan santai mengenai seksualitas dan gender. Pengennya sih, persoalan itu nggak lagi tabu buat diobrolin kayak obrolan warung kopi.
Sejak tahu terinfeksi HIV pada 2009, berapa lama waktu yang diperlukan untuk bangkit dan apa turning pointnya?
Kalau secara fisik, butuh waktu sekitar satu tahun untuk pemulihan kesehatan. Alhamdulillah, Karena dukungan penuh dari keluarga, treatment ARV yang dikonsumsi setiap hari atau konsultasi bulanan ke dokter jadi nggak begitu terasa berat. Mama dan papa bukan cuma mendukung untuk soal kesehatan, tapi mereka support sampai menjaga anak saya selama saya harus mencari uang. Ya maklumlah mereka jadi orangtua tunggal semenjak ditinggal meninggal suami.
Tapi secara mental, di awal tahu bahwa saya terinfeksi HIV itu butuh waktu cukup lama sekitar tiga tahun untuk menerima kondisi ini. Khususnya sampai akhirnya benar benar ikhlas, nggak mengeluh dan juga berani speak up cerita apa adanya tentang status HIV saya.
Yang bikin saya akhirnya memutuskan untuk bangkit adalah saat saya dipecat dari tempat kerja karena mereka tahu saya terinfeksi HIV. Di situ saya berpikir kalau begini terus (not stand up to fight), maka orang-orang akan terus memperlakukan saya dengan buruk. Di titik tersebut saya memutuskan untuk menjadi diri saya sendiri apa adanya. Saya mikir kalau saya diinjek-injek orang lain gimana saya bisa melindungi anak dan keluarga saya kalau ada yang menghina mereka hanya karena saya terinfeksi HIV.
Tapi sejujurnya sih sampai hari ini pun, rasanya saya masih membutuhkan waktu untuk menghadapi begitu banyak diskriminasi sehari-hari yang sangat menganggu. Saya masih harus menerima bahwa banyak layanan kesehatan yang diskriminatif pada ODHA, saya nggak bisa sembarangan ke dokter karena ada kemungkinan mereka akan menolak melayani saya.
[caption id="attachment_91440" align="alignnone" width="800"] Photo credit: @ayuma_morie[/caption]
Photo credit: @ayuma_morie[/caption]
Stigma soal HIV masih sangat lekat di masyarakat kita. Apa pengalaman paling buruk yang pernah dialami karena stigma itu?
Yang paling buruk adalah cara pandang masyarakat terhadap orang yang terinfeksi HIV. Kami semua dianggap sampah dan penyakit masyarakat. Padahal sejak kita duduk di bangku sekolah, pemerintah sama sekali nggak pernah memberikan informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Giliran pas kita terinfeksi HIV kita pula yang disalahkan.
Kalau pengalaman terburuk, sesungguhnya nggak ada pengalaman yang paling buruk. Semua bentuk diskriminasi yang pernah saya terima adalah hal buruk. Sama sekali nggak nyaman saat seharusnya lo bisa hidup normal kayak masyarakat lain, eh ini malah dibedakan. Nggak ada yang lebih buruk daripada diperlakukan berbeda atau tidak adil karena HIV.
Kalau contohnya ada banyak sih.. salah satunya nggak dilayani di rumah sakit hanya karena petugas kesehatannya tahu kalau saya ODHA. Atau sempat ditinggalkan oleh beberapa kawan karena mungkin mereka bingung dan nggak nyaman berkawan sama saya. Dulu bahkan keluarga besar (di luar keluarga inti) sempat canggung berhadapan sama saya, biasanya kalau ngobrol biasa aja, ini sempat diem-dieman.
Teh Ayu pernah bekerja sebagai pendamping Sebaya, apa hal terberat saat harus mendampingi sesama ODHA?
Semua orang yang terinfeksi HIV punya persoalan yang beda dan hampir semuanya berat. Saya nggak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Tapi kesamaan yang selalu muncul adalah persoalan penerimaan baik dari diri sendiri dan masyarakat serta keluarga. Itu yang bikin kebanyakan ODHA sulit untuk bangkit dan mau menjalani hidupnya dengan happy setelah terinfeksi HIV.
”Ya buat apa happy kalau ternyata keluarga ga bisa menerima kami karena terinfeksi HIV, atau ga ada perusahaan yang mau menerima kami bekerja untuk mereka”. Statement itu yang selalu terdengar setiap kali bertemu dengan teman-teman ODHA.
Hal lain yang juga menjadi mimpi buruk saat mendampingi teman-teman ODHA adalah mereka menganggap bahwa tidak ada lagi harapan hidup. Banyak yang menganggap bahwa saat seseorang sudah terinfeksi HIV mereka sudah pasti akan mati. Informasi itu yang sering membuat seseorang akan depresi dan merasa tidak ada harapan.
Apa yang membuat selalu semangat untuk berkampanye melawan stigma tentang ODHA?
Di tahun 2009 saat pertama kali kami mengetahui mengenai HIV, saya benar-benar merasa sendirian. Suami yang biasanya menjadi tempat bercerita tentang apapun terbaring di high care unit, dan akhirnya meninggal dunia. Saya tidak mungkin bisa langsung bercerita kepada keluarga atau sahabat-sahabat terdekat mengenai perasaan saya. Saya sangat takut ditolak atau diabaikan karena HIV. Dan ketakutan itu terjadi saat saya dipecat di kantor.
Saya merasa harus bisa membiasakan diri untuk bicara tentang HIV di semua ruang. Saya ingin hidup normal tanpa harus khawatir. Saya ingin orang membicarakan HIV atau melakukan pemeriksaan HIV seperti kita mau periksa darah biasa aja.
Saya ingin semua orang yang terinfeksi HIV punya kesempatan yang sama untuk bekerja, untuk sekolah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Saya ingin kita jadi diri kita sendiri tanpa harus diliatin atau diomongin orang karena HIV. Saya ingin keluarga dan anak saya merasa aman dan nggak perlu khawatir terus akan mendapat perlakuan buruk dari orang lain.
Jadi sampai kapanpun saya akan mati-matian ngasih tau ke orang lain bahwa membedakan orang lain karena apapun itu nggak bener. Termasuk memberi stigma dan diskriminasi pada ODHA.
Selain HIV, kamu juga pernah memperjuangkan obat Hepatitis C agar bisa diakses secara gratis. Boleh diceritakan apa motivasinya?
Ini salah satu dilema terbesar yang dirasakan beberapa teman ODHA yang punya dual diagnosis HIV-Hepatitis C. karena obat HIV saat ini gratis tapi nggak bisa mematikan virus HIV-nya, sedangkan Obat Hepatitis C itu terbukti bisa mematikan virus Hepatitis C tapi harganyaaaa ampun mahal banget. Nggak akan ada yang mampu untuk beli kayaknya deh. Saat itu obat Hepatitis C yang tersedia bernama interferon Alfa A, cara pemakaiannya disuntik. Selain harganya yang mahal, obat ini efek sampingnya luar biasa menyakitkan. Ini informasi dari banyak kawan yang sudah pernah menjalani treatment Interferon.
Sampai akhirnya saya dan tim di kantor saat itu (Indonesia AIDS Coalition), kami memang sering banget brainstorming dan baca banyak literasi tentang pengobatan. Kami dapat informasi bahwa di Amerika sudah ditemukan obat yang berbentuk tablet dan dikonsumsi dengan cara ditelan, namanya Sofaldi. Tapi obat itu memang masih mahal banget di Amerika. Lalu kami dapat informasi tambahan bahwa ada 3 negara yang membeli paten obat tersebut dan membuat generiknya, yang tentunya menjadi lebih murah dan lebih sedikit efek sampingnya. So we decided, let’s do it! Kita perjuangkan supaya Indonesia bisa punya obat ini juga.
Prosesnya cukup panjang dan melelahkan. Mulai dari mengumpulkan tim yang mau berjuang bersama kami, lalu mencoba obat tersebut tentunya dengan cara menyelundupkannya dari negara terdekat yakni India, kemudian mencari dokter yang mau mendampingi kami sampai treatment selesai. Sembari membuktikan bahwa obat itu worth it buat ada di Indonesia kami juga melakukan pendekatan advokasi lain seperti melakukan pemberian informasi secara massive lewat social media, kemudian membuat petisi di change.org. Termasuk membuat aksi damai pada tahun 2015 di kantor Kementerian Kesehatan di Kuningan dan kantor BPOM. Singkat cerita, we win!
Kini obat Hepatitis C merk Sofosbuvir sudah bisa diakses di Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dari obat Interferon. Meski masuk dengan akses khusus, tidak diperjualbelikan dengan bebas. But I know we can, dan ini adalah awal yang sangat luar biasa baik, di mana kami percaya bahwa suara pasien dan masyarakat yang bersatu dapat merubah kondisi menjadi lebih baik.
Kamu tertarik pada sexuality dan gender, apa isu penting yang sedang diperjuangkan?
This is funny, tiap denger kata seksualitas dan gender, saya merasa justru tahu tentang ini setelah terinfeksi HIV. Kayaknya saya nggak bakalan tahu apa-apa kalau saya baik-baik baik aja. Jadi HIV ini kemudian mempertemukan saya dengan banyak hal penting yang harusnya saya pelajari dari dulu untuk mencegah. HIV juga yang membuka mata bahwa hidup nih bukan cuma soal saya aja.
Tahun 2010 saya ikut training belajar tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Di sana saya sadar bahwa saya ga tau apa-apa soal diri saya. Bahwa selama ini, sejak kecil saya hidup dalam lingkungan pendidikan dan rumah yang mengatur bahwa perempuan itu punya banyak sekali keterbatasan. Nggak boleh begini dan begitu. Hidupnya cuma dipersiapkan buat jadi ibu dan istri yang baik.
Makanya saya berontak sih.. saya putusin buat nggak ngikutin aturan-aturan itu. Saya naik gunung, belajar naik motor, jadi ketua OSIS, ikut ekskul teater, Cuma pengen buktiin kalau perempuan itu bukan cuma urusan sumur, dapur, dan kasur. We are more than that.
[caption id="attachment_91443" align="alignnone" width="800"] Ayu bersama teman-teman di Panggung Minoritas. (Photo: @ayuma_morie)[/caption]
Ayu bersama teman-teman di Panggung Minoritas. (Photo: @ayuma_morie)[/caption]
Setelah sekitar delapan tahun terinfeksi HIV, saya sadar 70% sahabat saya adalah gay, lesbian, dan transgender. So fun! Meskipun saya harus menanggung resiko diomongin orang, dijelek-jelekin karena dianggap mendukung kelompok yang nggak bermoral. Hey! Come on, saya nih berteman sama siapa aja lho. Nggak memandang orientasi seksual mereka apa, agama atau etnis mereka, atau bahkan ekspresi gender mereka. Selama kita berteman baik, saya nggak ada masalah dengan kepribadian mereka. Malah itu yang bikin mereka jadi keliatan unik.
Lantas kenapa semakin kesini makin lantang bercerita dan bicara di banyak ruang tentang gender dan seksualitas. Ya saya cuma pengen orang-orang nih tau bahwa kita semua diciptakan Tuhan dengan segala keberagaman. Tuhan lho yang bikin kita nih, jadi kenapa kita harus ngambil tugas Tuhan untuk menghakimi orang lain karena mereka nggak sama dengan kebanyakan orang.
Itu kenapa akhirnya saya bikin pengajian gender bersama sahabat saya di panggung minoritas. Daripada ribut-ribut ngomongin politik, gender dan seksualitas saya rasa perlu mulai dibicarakan secara terang-terangan. Dan saya nggak takut.. karena saya nggak melakukan hal yang salah.
Apa tips kamu untuk menjalani hidup dengan bahagia?
Hmmm.. apa ya? Pada dasarnya saya nih orangnya bahagia bahagia aja. Tapi ya namanya manusia tetep punya persoalan dan ada waktunya sedih. Nah tiap kondisi itu datang, lagi ada cobaan dan masalah berat, saya nggak pernah pura – pura bahagia sih. Biasanya saya biarin aja deh tuh nangis sedih marah, saya pengen tubuh dan pikiran saya tahu bahwa rasa rasa yang nggak enak itu juga harus punya ruang. Jadi kita nggak meledak kalau disimpen lama.
Nah kalau sudah gitu saya coba untuk narik diri saya lagi untuk balik ke bumi. Cari kegiatan dan aktivitas yang biasanya saya seneng dan bikin happy. Ya kayak nonton Netflix, atau ke bioskop, makan makan, baca buku, hal hal sederhana yang sering kita lupain. Padahal bahagia itu tuh ada di dalam diri kita lho ga ada di mana-mana.
Tapi ada dua hal yang paling bisa jadi obat supaya saya terus bahagia. Pertama saya lagi seneng-senengnya gambar mandala, bisa dilihat di Instagram @ayuma_mandala.
Nah mandala ini sepertinya berhasil jadi medium jika saya merasa sedih atau marah. Setelah menggambar rasanya jadi jauh lebih baik. Yang kedua, nggak ada yang lebih bisa bikin saya merasa lebih baik selain Malika dan Febby. Suami dan anak saya, biarpun sering banget bikin rumah berantakan, tapi kalau ada mereka saya ngerasa aman dan jauh lebih tenang.
(Baca artikel kami sebelumnya: Grace Melia, Taking A Stand Against Rubella)
Share Article


POPULAR ARTICLE






COMMENTS