Sorry, we couldn't find any article matching ''
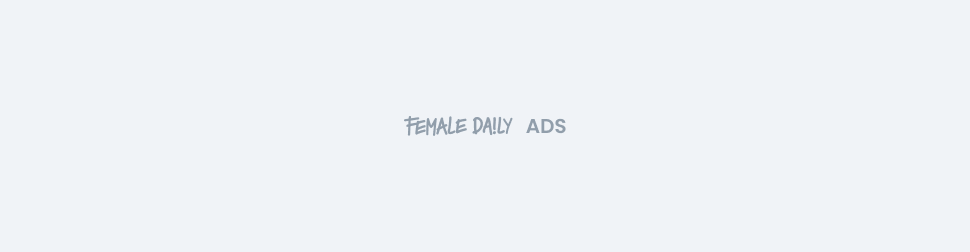
The Big Choice
Per hari ini, sudah hampir satu bulan saya menjalani hari-hari cuti dari titel karyawati, dan bertugas sebagai ibu yang 'ngepos' di rumah.
Saat mem'publikasi'kan kondisi saya ini, entah secara lisan atau melalui social media, reaksi pertama yang saya dapatkan, hampir selalu pertanyaan "Kenapa??" (sengaja pakai dua tanda seru untuk menyatakan ekspresi keheranan para penanya, hehe).

Seperti pernah saya ceritakan di sini, sudah lama saya mencita-citakan "banting setir." Bahkan gagasan menjadi SAHM sudah saya pikirkan sebelum menikah.
Saya ingat pembicaraan dengan calon suami beberapa tahun silam tentang parenting. Salah satu yang kami sepakati adalah kami tidak ingin anak diasuh oleh pembantu saja. Idealnya sih, saya ingin menjadi ibu yang mengasuh sendiri buah hatinya. Tapi saya masih ingin tetap bekerja setelah menikah, atau bahkan setelah punya anak, untuk mencapai kondisi paling memungkinkan dari segi finansial, dan paling nyaman dari segi kesiapan mental.
Setelah benar-benar menjadi orangtua, saya dihadapkan pada dilema yang umum dihadapi para ibu baru: Kembali ngantor atau tidak?
Kalau ingin mengikuti gambaran ideal tadi sih, inginnya memegang anak secara full-time, nursing kapanpun anak meminta, menerapkan attachment parenting, dan seterusnya. Tapi saya merasa kondisi rumah tangga kami saat itu belum 'kokoh' dari segi finansial. Dan saya tahu pasti bahwa saya belum siap secara mental. Kenapa?
Karena sebagian dari diri saya diam-diam lega ketika harus kembali ngantor. Saat ibu-ibu di kantor berkomentar dengan penuh empati pada hari pertama saya masuk setelah cuti hamil, "Duuh, pasti sedih, ya, ninggalin anak di rumah..." Dalam hati saya menjawab, "Sebenarnya enggak juga, sih."
Betapapun saya merasa bersalah karena merasa begitu, saya harus mengakui ada kelegaan bisa bekerja. Going to the office feels like a breath of fresh air. Saya bisa bertemu orang-orang, membicarakan hal selain popok dan pup, dan tidak perlu melulu nursing (dus, alasan untuk berganti pakaian selain daster dengan kancing di dada.)
Mungkin bisa dibilang ini adalah wujud ketidaksiapan saya untuk menjadi stay-at-home-mom. Seperti kita semua tahu, gambaran ideal bisa terdistorsi jika sudah dihadapkan dengan kenyataan :D
Lalu, kok sekarang 'nekat' mau jadi SAHM?
Hari demi hari yang saya lalui bersama anak saya memberikan saya pelajaran, untuk semakin mengenal diri saya, dan menyadari wujud relasi saya dengan anak.
Saya melihat bahwa anak saya lebih clingy kepada oma-nya.
Saya melihat bahwa yang tertanam pada dirinya adalah pola asuh oma-nya yang bersama dia 12 jam sehari 5 hari seminggu.
Saya menyadari bahwa saya kekurangan kesabaran setelah menempuh 4-6 jam perjalanan dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Saya cenderung cranky menghadapi 'kesalahan' khas kanak-kanaknya.
Hampir setiap hari (kerja), saya hanya sanggup "berbasa-basi" sejenak dengan anak sebelum akhirnya tidur membawa kelelahan.
Saya tergugu saat menyadari bahwa my kid deserves better. Kini anak saya telah memasuki masa di mana porsi pengasuhan lebih dititikberatkan untuk me-nurture kemampuan psiko-emosional anak, selain kognitif dan kesehatan fisiknya. Ini adalah saat untuk menanamkan kebiasaan baik, menumbuhkan kemandirian, dan menancapkan pondasi kepribadian dan karakternya. Saya bertanya pada diri sendiri, "Sebaik apa kualitas pengasuhan yang dapat saya berikan dengan tetap bekerja? Dan sebaik apa jika saya berhenti bekerja?"
Untuk menjawab pertanyaan, saya menggali diri sendiri. Gambaran ideal tentang pengasuhan sudah tertanam di diri saya sejak lama. Saya sendiri dibesarkan oleh ibu bekerja, dan semakin dewasa, saya semakin menyadari bahwa she and I are so much alike. She was so stressed out when trying to balance her work and personal life. Seperti yang saya rasakan sekarang. Saya sadar, pasti ada banyak ibu-ibu bekerja di luar sana yang secara fisik maupun emosi menjalani apa yang saya jalani dan tetap bisa melakukan performa yang prima. Memiliki jumlah waktu serta kesibukan yang sama dengan saya, dan tidak mengeluh. Tapi, manusia diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Kita unik, dengan karakter, kepribadian, dan cara kita menjalani hidup.
Saya ingin mencoba melakukan yang terbaik, dalam pandangan dan dengan cara saya. Dan kebetulan saja, dengan kondisi sebagai pekerja 8 to 5 (meski dalam praktiknya 5 to 8), saya merasa tidak bisa mencapai kualitas pengasuhan yang ingin saya berikan kepada anak dengan tetap bekerja.

Saya sendiri percaya akan paham "quality over quantity." Saya bertaya pada diri sendiri, untuk apa secara fisik bersama anak berjam-jam tapi tetap tidak mampu membangun relasi yang baik, apalagi kualitas pengasuhan yang baik?
Seperti halnya apa manfaat ikut banyak seminar parenting jika tidak bisa mengubah diri?
Dan, untuk apa punya cita-cita jika tidak berusaha diwujudkan?
Saat kuliah, saya selalu membuat target pencapaian IP. Prinsip saya, berikan dulu yang 'terbaik,' end-result tidak perlu dipusingkan. Karena penentu berapa besar nilai bukan cuma usaha kita, tapi ada juga faktor x, y, z. Bisa saja saat ujian kita sakit. Bisa saja materi yang kita baca tidak diuji. Ada puluhan bahkan ratusan skenario lain. Yang terpenting adalah berusaha, melakukan yang terbaik menurut saya.
That way, I won't ask myself at the end of day, "What if i had done this instead of that? What would have happened if i tried harder?"
Maka pelan-pelan saya mencoba menata hati agar berjalan ke arah usaha 'terbaik' itu. Saya mencoba less-attached kepada kenikmatan-kenikmatan yang didapat dari kantor (dalam wujud gaji, terutama, hehe). Saya bahkan berkonsultasi dengan psikolog keluarga agar bisa mendapatkan masukan yang paling sesuai dengan kebutuhan saya. Saya juga banyak membaca testimonial ibu-ibu yang "banting setir" supaya mendapat gambaran realistis, misalnya bagaimana beradaptasi dengan perubahan dunia yang tadinya 'luas' menjadi 'sempit?' Saya juga dapat banyak masukan untuk memanfaatkan waktu dan status sebagai SAHM.
Dari situ, saya menyadari bahwa yang paling penting adalah tidak defensif, buka hati dan rasakan. Kekhawatiran orang-orang terdekat muncul karena mereka sayang dan ingin yang terbaik bagi kita. Komentar-komentar yang kesannya negatif, muncul mungkin karena pengalaman negatif namun bisa dijadikan pelajaran dan alarm pribadi.
Pada akhirnya, no one knows how it's gonna turn out. Namanya juga usaha :) Seperti saat membuat target tadi, yang paling penting, lakukan bagian berusahanya dulu. I do my part and let God do the rest. Pretty much a leap faith, right?
Kesimpulannya, saya ingin mencoba melakukan yang terbaik dalam VERSI saya, dan kebetulan saja, dengan segala 'konspirasi' kosmik yang telah membentuk kepribadian dan jalan hidup saya, saya memilih ini.
Saat sedang membuat tulisan ini, saya teringat pada adegan di film Mona Lisa Smile yang menurut saya, bisa menggambarkan apa yang saya coba paparkan. Joan Brandwyn yang diperankan oleh aktris Julia Stiles, adalah karakter perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Padahal ia mendapat pendidikan, dan kesempatan, untuk bisa berkeluarga DAN berkarir di masa di mana hak perempuan untuk berkarir sulit didapatkan. Saat dosennya menyayangkan pilihan Joan, dia berkata,
"You stand in class and tell us to look beyond the image, but you don't. To you a housewife is someone who sold her soul for a center hall colonial. She has no depth, no intellect, no interests. You're the one who said I could do anything I wanted. This is what I want."
Meski saya tidak se-jumawa Joan Brandwyn, tapi dia memang mewakili apa yang ingin saya sampaikan. I went to school, had my options, and this is what i want now. What's yours, Mommies? :)
Share Article


POPULAR ARTICLE




COMMENTS