
“Bu, Zia mau ikut Endru ke Sekolah Minggu. Boleh, ya, Bu?” rengek Zia, anak saya yang berumur 4 tahun, di suatu Minggu pagi.
Duh, ini dia datang lagi salah satu dari sekian ribu pertanyaan anak-anak yang membuat pusing orangtua untuk mencari jawabannya. Kebetulan keyakinan keluarga kami dan keluarga Endru berbeda.
“Ndak bisa, Nak. Zia tidak bisa ikut Endru ke Sekolah Minggu.”
“Kenapa, Bu?”
“Karena Endru mau belajar di sana, seperti Zia belajar mengaji atau ke sekolah malam-malam (saat itu kami sekeluarga pergi Tarawih di masjid sekolah Zia). Endru dan Zia, kan, agamanya berbeda.”
“Oh, begitu.”
Kejadian di atas terjadi ketika bulan puasa 2012, di mana Zia dan Endru berkawan karib di kompleks perumahan kami. Zia sedang dalam umurnya memiliki curiosity tinggi sering bertanya apa dan kenapa. Tahun ini adalah tahun pertama Zia belajar di sekolah yang berbasis keyakinan kami. Tahun ini mungkin Zia akan menyadari bahwa di penghujung tahun ini kami sekeluarga akan berkumpul dengan keluarga besar untuk acara arisan periodik yang selalu diselenggarakan pas di hari Lebaran dan Natal (di rumah keluarga tertua yang merayakan hari besar tersebut). Mungkin dia akan menyadari kalau arisan di rumah Eyang Buyut Senayan, dia akan bertemu yang namanya ketupat dan “salam tempel”, sedangkan arisan di rumah Eyang di Pulomas, dia akan melihat pohon Natal dan hadiah-hadiah di bawahnya. Saya dan ayahnya sedang menyiapkan diri jika bertemu pertanyaan seputar perbedaan keyakinan dalam keluarga kami yang kebetulan beragam.
Kami berdua memiliki keyakinan bahwa sikap yang akan membentuk anak-anak ketika mereka menghadapi dunia luar (sekarang maupun kelak ketika dewasa) adalah sebagian besar hasil pembentukan dari rumah kami. Harapannya kelak anak-anak bisa bertoleransi dengan perbedaan di sekelilingnya secara bijaksana dan saling menghormati. Suatu hal wajar dalam sebuah keluarga pasti orang tua menginginkan anak-anak dan keturunannya mengikuti keyakinan yang dianut orangtuanya, meskipun kelak akan menjadi pilihan hati mereka masing-masing. Maka daripada itu, kami berdua saat ini sedang berputar otak bagaimana menerangkan yang namanya perbedaan keyakinan dan perbedaan cara beribadah tanpa harus menjelek-jelekkan agama atau keyakinan yang tidak kami anut.
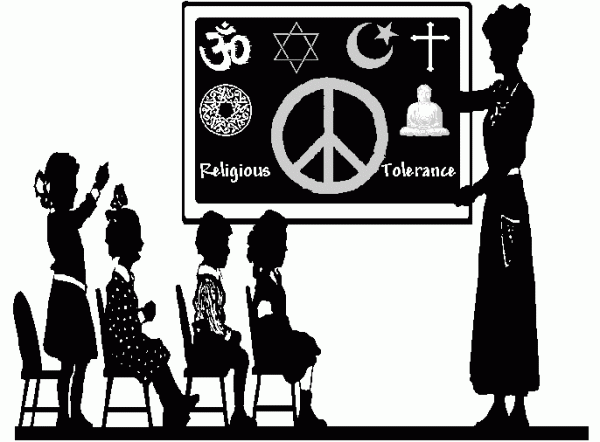 *gambar dari sini
*gambar dari sini
Saya ingat ketika saya pertama kali akan masuk sekolah menengah yang kebetulan berbasis bukan agama yang saya anut. Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah terbaik di kota saya, orang tua saya berharap saya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Guru mengaji ibu saya dan ibu-ibu di kompleks kami tinggal datang ke rumah, membawa beberapa buku tentang kisah para nabi kami. Beliau menerangkan sesuai agama yang kami anut, tanpa membanding-bandingkan bagaimana agama lain menceritakan kisah para nabi tersebut. Sungguh bijak cara beliau, memperkaya ilmu agama saya tanpa menjelek-jelekkan agama lainnya.
Kelak, ketika nalar Zia semakin berkembang, kami harus menjelaskan sesuai dengan usianya dan cara dia dapat menangkap dan mengolah masukan dari kami. Hal tersebut harus dilakukan sedikit demi sedikit.
Minggu lalu ketika kami berada di pusat perbelanjaan, kebetulan ada acara perayaan Natal dengan pertunjukan tokoh Sylvanians dengan iringan lagu Natal. Zia bertanya kepada saya:
“Ibu, Zia mau nyanyi dan nari sama anak-anak yang di bawah itu.”
“Ndak bisa, Nak.”
“Kenapa, Bu?”
“Karena, mereka seperti Endru sedang merayakan hari rayanya, seperti Zia merayakan hari Idul Adha kemarin. Kita tidak boleh mengganggu mereka yang sedang merayakan, sama seperti Zia kalau sedang mengaji atau salat, kan, tidak mau diganggu juga.”
“O, ya, Bu. Zia lupa, kita, kan, tidak boleh mengganggu orang lain.”
Mungkin kita punya cara yang berbeda, but we all dream a better place to live in this world without any prejudice and war, right? Jika kita bisa menghormati yang lain, yang lain pun akan menghormati kita juga. Bagaimana Mommies, mungkin ada masukan cara menerangkan suatu perbedaan keyakinan?